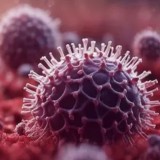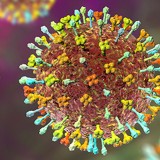TIMES JABAR, JAKARTA – Indonesia sering kali membanggakan pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Namun, ironi muncul ketika rakyat dituntut sekolah setinggi mungkin, sementara elit politik yang menduduki kursi-kursi strategis pemerintahan justru tidak selalu menunjukkan standar pendidikan yang layak.
Guru saja disyaratkan minimal bergelar sarjana, buruh pabrik pun sering diwajibkan melampirkan ijazah S1 untuk sekadar bekerja, tetapi anggota legislatif yang mengatur hajat hidup orang banyak bisa cukup bermodalkan ijazah SMA. Kontras ini menjadi cermin ketidakadilan sistemik yang mengguncang rasa keadilan publik dan menyingkap rapuhnya meritokrasi di negeri ini.
Data terbaru memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1,01 juta pengangguran lulusan perguruan tinggi pada tahun 2025. Angka ini bagian dari total pengangguran nasional yang mencapai 7,28 juta orang, atau 4,76% dari total angkatan kerja.
Ironisnya, di saat para sarjana sulit mencari pekerjaan, kursi parlemen dan jabatan politik strategis justru bisa diisi oleh mereka yang hanya lulusan sekolah menengah. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 7% anggota DPR RI periode 2019 - 2024 adalah lulusan SMA atau sederajat. Dengan kata lain, ada jurang besar antara standar yang dikenakan pada rakyat biasa dengan standar yang berlaku bagi elit politik.
Persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar soal ijazah. Pendidikan tinggi idealnya menjadi indikator kapasitas intelektual seorang pemimpin. Lulusan S1 setidaknya sudah memahami teori dan metodologi dasar dalam bidangnya, S2 mulai menguji teori, sementara S3 menciptakan gagasan baru.
Tingkat pendidikan memang mempengaruhi cara pandang dan kapasitas berpikir seseorang. Dengan demikian, perdebatan soal penting atau tidaknya pendidikan tinggi bagi pemimpin tidak bisa direduksi semata ke urusan formalitas, tetapi menyangkut kualitas kebijakan yang akan lahir dari tangan-tangan pengambil keputusan.
Filsuf Yunani, Plato, sejak lama sudah memberi kritik keras terhadap demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi memungkinkan siapa saja naik ke tampuk kekuasaan, terlepas dari kualitasnya.
Demokrasi rawan dipenuhi mereka yang pandai bersilat lidah, menjanjikan banyak hal, dan pintar mencuri perhatian publik, meski miskin kapasitas intelektual. Kritik Plato ini kini terasa relevan dengan kondisi Indonesia.
Demokrasi di sini sering kali berubah menjadi ajang kontestasi popularitas, bukan adu kapasitas. Elit politik tidak selalu dipilih karena kemampuan mengelola negara, tetapi lebih karena uang, nama besar, atau daya tarik panggung.
Konsekuensi dari rendahnya standar pendidikan di kalangan elit politik sangat serius. Kebijakan publik yang lahir sering kali tidak dibangun di atas riset, teori, atau analisis matang, melainkan sekadar pencitraan untuk terlihat “kerja”.
Kebijakan pun rentan bersifat reaktif dan dangkal, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Lebih parah lagi, rendahnya standar pendidikan kerap beriringan dengan menguatnya nepotisme.
Jabatan politik sering diwariskan pada keluarga atau kerabat, meski tanpa kualifikasi memadai. Praktik ini menutup peluang bagi mereka yang sesungguhnya lebih kompeten, sekaligus memperdalam krisis meritokrasi di Indonesia.
Dalam konteks teori politik modern, masalah ini dapat dipahami melalui konsep justice as fairness yang diperkenalkan John Rawls. Rawls menekankan bahwa keadilan dalam masyarakat terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan usaha, bukan karena privilese atau status sosial.
Realitas di Indonesia jelas bertolak belakang: jabatan publik tidak selalu diraih lewat kapasitas atau kompetensi, melainkan diwariskan melalui politik dinasti atau modal finansial. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem politik kita gagal menjunjung prinsip keadilan prosedural yang mestinya menjadi fondasi demokrasi.
Kritik terhadap fenomena ini bukan berarti meremehkan mereka yang hanya lulusan SMA. Banyak tokoh besar di masa lalu memang tidak mengenyam pendidikan tinggi, namun perlu diingat bahwa konteks sosial, akses pengetahuan, dan tuntutan zaman sudah berbeda.
Lulusan SMA pada masa kini jelas tidak bisa disamakan dengan lulusan SMA pada masa lalu, ketika jalur belajar informal dan otodidak masih bisa menyalakan api intelektualitas yang besar. Di era globalisasi dengan tantangan kompleks seperti sekarang, pemimpin yang hanya berbekal pendidikan menengah jelas terlalu rapuh untuk memikul beban negara.
Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, memberi kerangka lain untuk melihat problem ini melalui konsep cultural capital. Pendidikan adalah salah satu bentuk modal kultural yang menentukan posisi seseorang dalam masyarakat.
Semakin tinggi modal kultural yang dimiliki, semakin besar peluang individu untuk memengaruhi kebijakan dan kehidupan sosial. Namun, di Indonesia, modal kultural ini justru sering diabaikan ketika bicara politik.
Yang lebih dominan adalah modal ekonomi dan jaringan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi kita berjalan pincang. Pemimpin dipilih bukan karena kapasitas intelektualnya, melainkan karena daya beli politiknya.
Krisis meritokrasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari sistem pemerintahan yang ideal. Meritokrasi, yang seharusnya menempatkan orang berdasarkan kapasitas dan prestasi, justru kalah oleh oligarki, dinasti, dan politik uang.
Demokrasi Indonesia masih belum mampu menyaring kualitas calon pemimpin dengan baik. Publik pun ikut andil ketika lebih memilih figur populer atau bermodal besar daripada figur yang benar-benar berkapasitas.
Ke depan, Indonesia perlu berani membenahi standar pendidikan bagi elit politiknya. Minimal gelar sarjana seharusnya menjadi syarat bagi mereka yang ingin menduduki kursi legislatif maupun eksekutif strategis.
Partai politik pun harus bertransformasi, bukan lagi mengusung calon berdasarkan popularitas semata, melainkan melalui proses kaderisasi yang menekankan kapasitas intelektual, pengalaman, dan integritas. Tanpa itu semua, demokrasi akan terus melahirkan pemimpin yang salah urus dan kebijakan yang jauh dari substansi.
Indonesia kerap memimpikan diri sebagai negara besar dengan visi kemajuan. Namun, bagaimana mungkin mimpi itu terwujud bila kualitas pemimpinnya tidak dibangun di atas fondasi pendidikan yang kokoh?
Krisis meritokrasi bukan sekadar soal ijazah, melainkan soal arah bangsa. Jika standar pendidikan pemimpin terus diabaikan, maka Indonesia sedang mempertaruhkan kualitas kebijakan publik, masa depan generasi muda, bahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.
Plato benar ketika menyebut demokrasi bisa jatuh ke tangan mereka yang pandai berbicara tetapi miskin kapasitas. Tanpa keberanian memperbaiki standar pendidikan elit politik, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran demokrasi prosedural tanpa substansi.
***
*) Oleh : Rikza Anung Andita Putra, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |