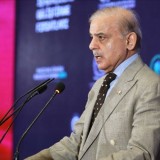TIMES JABAR, JAKARTA – Setiap kali krisis sosial atau gejolak politik mengguncang republik, pejabat publik selalu punya mantra yang siap diucapkan: fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kalimat itu, berulang kali, menjadi semacam jimat kolektif membius pasar, menenangkan investor, sekaligus menenangkan hati pemerintah sendiri.
Pertanyaan mendasarnya: apakah resiliensi ekonomi bisa direduksi sekadar pada pertumbuhan lima persen, inflasi yang terjaga, atau cadangan devisa yang cukup?
Douglas North (1990) menegaskan bahwa daya tahan ekonomi ditentukan oleh kualitas institusi, bukan sekadar indikator makro. Resiliensi adalah soal rules of the game bagaimana birokrasi menata aturan, melaksanakan pelayanan, dan mengelola sumber daya publik. Tanpa reformasi birokrasi, angka-angka makro hanyalah kulit luar dari pohon rapuh yang mudah tumbang saat angin kencang datang.
Pemerintah punya alasan untuk percaya diri: pertumbuhan stabil, inflasi rendah, defisit anggaran terkendali, dan cadangan devisa sehat. Bahkan investasi asing masih masuk meski protes publik meluas. Tetapi di balik angka-angka itu, kehidupan rakyat justru kian sulit. Harga pangan terus menanjak, biaya pendidikan melonjak, dan akses kesehatan makin memberatkan.
Paradoks ini memperlihatkan jurang antara makro dan mikro. Dani Rodrik (2018) menekankan bahwa stabilitas makro tanpa institusi domestik yang melindungi rakyat hanya melahirkan resiliensi semu.
Di Indonesia, birokrasi masih lebih sigap melayani investor besar ketimbang petani kecil atau pelaku UMKM. Maka tidak heran jika rakyat kerap merasa “resiliensi” hanya milik elit, sementara mereka terdesak dalam keseharian.
Reformasi birokrasi digulirkan sejak dua dekade lalu. Tujuannya mulia: mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan. Namun, kenyataannya, transformasi ini masih separuh hati. Budaya patrimonial tetap kuat, perizinan masih berbelit, dan tata kelola fiskal kerap dijadikan instrumen politik jangka pendek.
Francis Fukuyama (2013) menekankan bahwa negara yang kuat bukanlah negara dengan anggaran besar, melainkan dengan kapasitas birokrasi yang mampu menegakkan aturan dan melayani publik secara efektif.
Indonesia sendiri, sayangnya masih terjebak pada birokrasi yang lamban bertransformasi. Akibatnya, setiap kali krisis datang, respons negara bersifat reaktif bansos dadakan, subsidi sementara bukan solusi sistemik yang menguatkan daya lenting rakyat.
Masalah resiliensi kita bersumber dari tata kelola yang belum kokoh. Pertama, birokrasi kerap menjadi arena rente. Alih-alih efisien, banyak kebijakan ekonomi tersandera kepentingan politik. Daron Acemoglu dan James Robinson (2012, Why Nations Fail) menyebut kondisi ini sebagai jebakan institusi eksklusif: aturan dibuat untuk memperkaya segelintir, bukan memperluas kesejahteraan.
Kedua, regulasi yang tumpang tindih memperlemah iklim usaha. Alih-alih menjadi fasilitator, birokrasi justru sering menjadi penghambat industrialisasi.
Ketiga, tata kelola lingkungan masih abai. Padahal, resiliensi ekonomi tidak mungkin terwujud jika sumber daya alam hutan, sungai, dan lahan dikuras tanpa kendali. The Dasgupta Review (2021) menegaskan bahwa natural capital harus masuk dalam kerangka kebijakan ekonomi. Tanpa itu, banjir, kekeringan, dan krisis pangan akan terus melemahkan daya tahan rakyat.
Resiliensi dan Keadilan Sosial
Amartya Sen (1999, Development as Freedom) mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar akumulasi PDB, melainkan perluasan capabilities kemampuan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat. Resiliensi ekonomi Indonesia, jika ingin otentik, harus menjamin akses pada pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak.
Namun, birokrasi kita masih lebih sering menyalurkan bansos saat krisis ketimbang membangun sistem perlindungan sosial yang permanen. Raghuram Rajan (2019, Foreign Affairs) mengkritik praktik semacam ini sebagai procyclical populism: kebijakan ekonomi yang reaktif, bukan preventif, sehingga rakyat tetap rentan.
Di sinilah letak persoalan mendasar: resiliensi bukan sekadar angka di layar, melainkan rasa keadilan yang dirasakan rakyat. Jika rakyat merasa tertinggal, protes sosial menjadi alarm penanda bahwa resiliensi negara tidak sinkron dengan resiliensi masyarakat.
Jalan Panjang Reformasi
Apa yang harus dilakukan agar resiliensi tidak berhenti sebagai mitos statistik? Pertama, reformasi birokrasi harus diperbarui. Digitalisasi layanan penting, tetapi jauh lebih penting adalah membangun budaya meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Aparatur sipil negara harus dipandang sebagai mesin pembangunan, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Kedua, disiplin fiskal harus dipertahankan dengan orientasi publik. Anggaran negara tidak boleh menjadi korban manuver politik. Prioritasnya adalah pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bukan proyek mercusuar yang hanya mempercantik laporan.
Ketiga, industrialiasi inklusif harus digerakkan. Hilirisasi mesti dipadukan dengan kebijakan yang membuka ruang bagi UMKM, koperasi, dan ekonomi desa. Resiliensi ekonomi baru bermakna jika struktur ekonomi melebar, bukan menyempit di tangan segelintir konglomerasi.
Keempat, ekologi pembangunan harus dijaga. Resiliensi tidak mungkin tercapai jika pembangunan mengabaikan daya lenting alam. Kapital alam adalah pondasi resiliensi jangka panjang; tanpa itu, setiap angka pertumbuhan hanya fatamorgana.
Resiliensi ekonomi Indonesia tidak bisa lagi dimaknai semata sebagai stabilitas makro. Ia harus dipahami sebagai kapasitas negara untuk melindungi rakyat, dan itu hanya mungkin bila birokrasi berfungsi sebagai institusi publik yang inklusif.
Indonesia memiliki modal besar: bonus demografi, kekayaan alam, dan ruang fiskal yang relatif sehat. Tetapi modal itu akan sia-sia bila reformasi birokrasi tertunda. Tanpa birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan, resiliensi hanya menjadi mantra di podium.
Resiliensi sejati adalah ketika dapur rakyat mengepul tanpa cemas, ketika petani menjual panen dengan harga adil, ketika anak-anak desa dapat bermimpi menembus horizon masa depan.
Dengan kata lain, resiliensi ekonomi sejati adalah resiliensi yang bersenyawa dengan reformasi birokrasi, dan pada akhirnya mewujudkan cita-cita konstitusi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
***
*) Oleh : Fahmi Prayoga, S.E., Economist, Public Policy Analyst, and Researcher of SmartID.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Resiliensi Ekonomi
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |