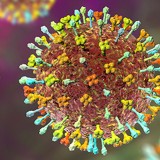TIMES JABAR, TANGERANG – Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya menjadi ruang pemersatu keyakinan bukan alat ukur siapa yang paling ber-Tuhan. Namun, di tengah hiruk-pikuk budaya digital, nilai itu kini diuji.
Tayangan Trans7 yang dianggap melecehkan simbol pesantren menjadi contoh bagaimana ruang publik kehilangan empati. Seruan #BoikotTrans7 pun menggema, bukan semata karena tersinggung, tetapi sebagai bentuk perlawanan moral terhadap budaya yang makin jauh dari adab.
Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah jantung peradaban Islam Nusantara tempat di mana iman, akhlak, dan ilmu berpadu menjadi satu napas kehidupan. Di sana, agama bukan hanya diajarkan, tapi dihidupi.
Maka ketika simbol pesantren dijadikan bahan olok-olok, itu bukan sekadar kekeliruan produksi konten. Itu luka. Luka terhadap sejarah panjang spiritual bangsa yang tumbuh dari kesederhanaan dan keikhlasan para kiai dan santri.
Masalahnya, sebagian media kini kehilangan jarak etik antara hiburan dan penghormatan. Atas nama kreativitas dan rating, nilai religius dan budaya lokal sering kali dikorbankan. Padahal bangsa ini berdiri di atas keseimbangan antara agama dan budaya.
Para pendiri bangsa KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, hingga Soekarno meletakkan dasar bahwa kemerdekaan lahir dari iman, adab, dan kesadaran moral, bukan dari sensasi atau kelucuan kosong.
Sila pertama tidak berhenti pada pengakuan teologis. Ia adalah komitmen moral untuk menghormati setiap ekspresi keimanan termasuk nilai-nilai pesantren.
Menjadikan simbol agama sebagai bahan candaan bukanlah kebebasan berekspresi, tetapi bentuk kaburnya batas antara kreativitas dan penghinaan. Kebebasan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari ketidaksopanan.
Pesantren justru contoh terbaik dari keterbukaan budaya. Islam Nusantara tumbuh dari dialog antara nilai Islam dan tradisi lokal. Namun, keterbukaan itu tak berarti membiarkan sakralitas diinjak atas nama hiburan. Sebab di pesantren, doa bukan formalitas, dan zikir bukan tontonan keduanya adalah bagian dari jiwa bangsa.
Gelombang boikot terhadap Trans7 perlu dibaca sebagai koreksi moral, bukan sebagai bentuk anti kritik. Masyarakat hanya menuntut empati: agar media kembali menjadi penjaga moral publik, bukan pelaku yang melukai. Ini bukan tentang siapa yang paling suci, tetapi tentang siapa yang masih punya rasa hormat terhadap nilai spiritual.
Mungkin, inilah ujian sejati sila pertama di era kebebasan budaya mampukah kita menegakkan nilai Ketuhanan di tengah budaya yang kian menjauh dari kesakralan? Media punya pilihan: menjadi ruang pencerahan, atau panggung olok-olok yang meninggalkan luka.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati akar moralnya sendiri. Dan pesantren dengan kesederhanaannya adalah akar itu. Menginjaknya sama saja mencabut diri dari identitas keindonesiaan.
***
*) Oleh : Septiani Agustina, Mahasiswa Ilmu Manajemen Universitas Pamulang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |