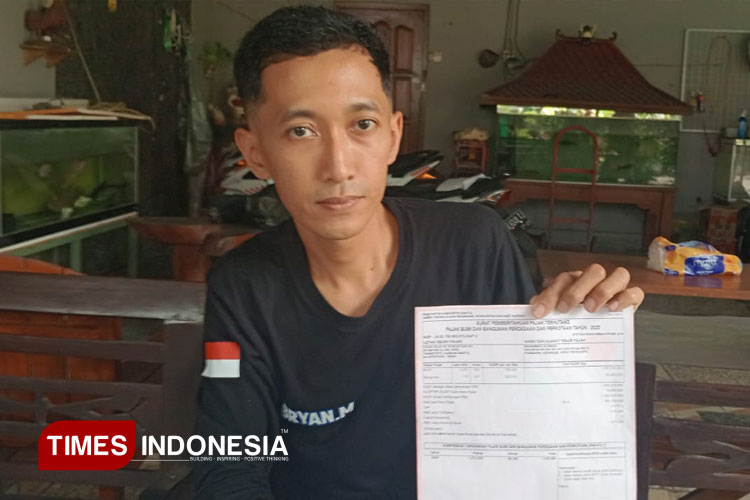TIMES JABAR, SUMATERA – Secara teoritis konstitusi memang idealnya diperbarui setiap 19 tahun. Karena dinamika praktik ketatanegaraan berbanding lurus dengan dinamisnya perkembangan sosial, budaya dan politik. Namun, perubahan konstitusi secara konvensional juga berbanding lurus dengan suasana politik dan langgam kekuasaan yang menjadi penentu hasil amandemen.
Kemunduran
Empat kali amandemen UUD 1945 memang tidak sempurna. Misalnya legislasi yang melibatkan Presiden. Praktik pembentukan undang-undang di Indonesia pasca amandemen masih mengakomodir model legislasi UUD 1945 lama yang melibatkan eksekutif.
Di mana karakter pemerintahan parlementer itu menyimpang dari kesepakatan awal amandemen yang hendak memperkuat sistem presidensial. Model legislasi ini menghasilkan kerumitan lain, sebab sekalipun UUD 1945 memperbolehkan Presiden untuk tidak menandatangani suatu rancangan undang-undang. Dalam tempo 30 hari rancangan undang-undang itu tetap saja berlaku.
Praktik ini begitu jauh dari teori presidensialisme yang memberi kekuatan konstitusional kepada Presiden untuk menolak rancangan undang-undang.
Namun, bukan berarti amandemen kelima adalah obat mujarab. Karena maksud yang melatar belakanginya kian menjauhkan Indonesia dari praktik presidensial.
Bahkan tujuan amandemen kelima patut diwaspadai, karena dilakukan di tengah suasana politik dan langgam kekuasaan yang tidak baik-baik saja. Amandemen kelima dapat dipersoalkan dengan melihat 5 poin rencana perubahan yang ditujukan untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Artinya, bila amandemen kelima bergulir sama halnya dengan mengembalikan desain penyelenggaraan negara kepada bentuk yang pernah dimanfaatkan Orde Baru untuk menjalankan pemerintahan tangan besi sepanjang tiga dekade. Dengan alasan mampetnya penyelenggaraan visi pembangunan tanpa GBHN.
Ketua DPD dan Ketua MPR menyimpulkan amandemen kelima untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara seolah solusi terbaik. Sedangkan pangkal persoalan pembangunan terjadi di pusat. Antara Bappenas yang menyusun rencana pembangunan dengan Kementerian Keuangan yang menyusun anggaran, antara visi dan eksekusi.
Dalih ringkih itu ditambah dengan maksud mengembalikan peran MPR untuk memilih Presiden yang melenceng jauh dari karakter sistem presidensial. Pada dasarnya presidensialisme mengupayakan Presiden di posisi sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Sedangkan pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR secara otomatis mengakibatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan negara dialihkan kepada MPR, dan praktik itu merupakan karakter sistem parlementer.
Praktik inilah yang diterapkan pada UUD 1945 lama, dan dari sinilah terlihat adanya keanehan UUD 1945 lama yang modelnya hendak diberlakukan kembali. Keanehan itu ditenggarai oleh desain yang menciptakan jalannya pemerintahan secara presidensial namun mekanisme pertanggungjawabannya secara parlementer.
Permasalahan yang muncul kemudian tidak hanya seputar sistem pemerintahan di tataran teoritis. Namun juga menyangkut penggerusan daulat rakyat yang kembali dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Bukankah reformasi yang berujung amandemen itu menghendaki pemilihan langsung sebagai upaya pelibatan rakyat secara aktif untuk menentukan pemimpin?
Tragedi
Persoalan lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah pengalaman amandemen yang diawali tragedi 25 tahun lampau. Reformasi berdarah itu bukan sekadar gerakan massa yang sekonyong-konyong meledak setelah terjadi krisis moneter.
Ia tidak lain adalah buah dari beringin kekuasaan berusia 30 tahun yang ledakannya di pantik oleh inflasi. Upaya kolektif untuk memperbaiki tatanan bernegara melalui amandemen lah yang memanfaatkan momentum tragedi bertajuk reformasi, bukan sebaliknya.
Akan menjadi hal yang patut diwaspadai nantinya bilamana amandemen kelima bergulir di tengah langgam kekuasaan yang kian menyerupai despotisme Orde Baru tanpa didahului tragedi. Seperti yang sudah-sudah, dalam sejarahnya negara ini selalu membutuhkan sebuah peristiwa sebagai perekat kolektif untuk kemudian bersama-sama memperbaiki yang patut diperbaiki.
Di Indonesia, tragedi lah yang melahirkan amandemen, jangan sampai amandemen yang melahirkan tragedi. Bila itu terjadi, tragedi justru kehilangan perekat kolektif dan malah menghasilkan perpecahan yang masif. Ketika itu Indonesia tinggal sebuah nama dalam catatan sejarah dunia.
***
*) Oleh : Ilhamdi Putra (Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Manajer Riset LBH Pers Padang)
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : |
| Editor | : Hainorrahman |